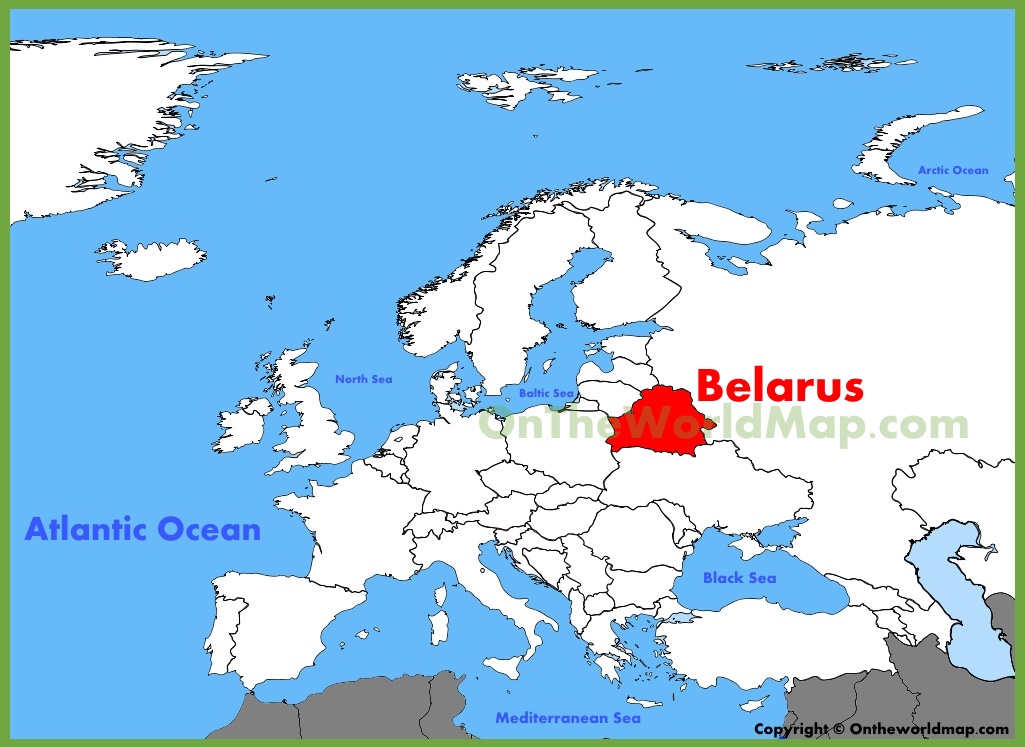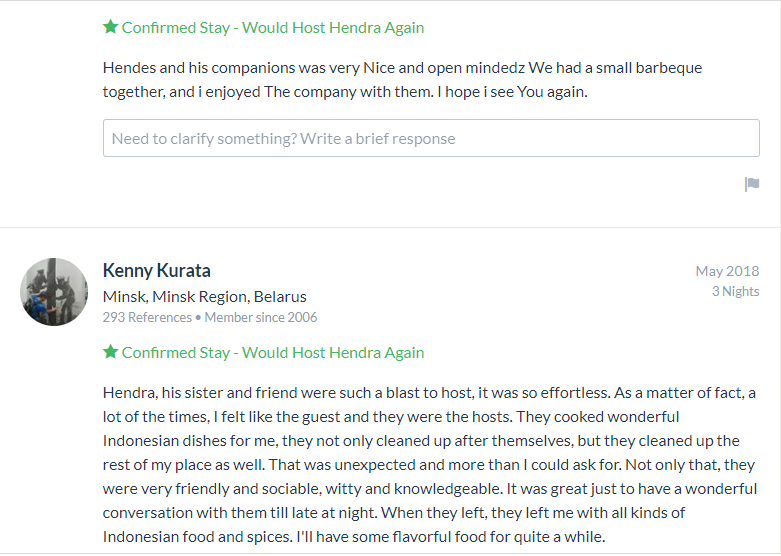Nagorno-Karabakh?? Apaan tuh? Itu dimana? Kok gue baru denger?
Jadi begini, pemirsa. Once upon a time, ketika saya masih berstatus mahasiswa jurusan Kajian Wilayah Eropa, saya sempat mempelajari konflik antara dua negara di bumi Kaukasia (Azerbaijan dan Armenia). Tersebutlah sebuah teritori milik Azerbaijan bernama Nagorno-Karabakh. Secara geografis, Nagorno-Karabakh terletak di selatan pengunungan Kaukasus, sekitar 270km di barat kota Baku, ibukota Azerbaijan. “Negara” ini merupakan negara landlocked yang dikelilingi oleh deretan pengunungan tinggi dengan luas sekitar 4400 km persegi. Karena konflik yang berkepanjangan antara Azerbaijan dan Armenia, Nagorno-Karabakh akhirnya memutuskan untuk memerdekakan diri melalui sebuah referendum.
Namun sayangnya kemerdekaan ini nggak diakui oleh dunia–hanya ada segelintir negara (termasuk Armenia dan Australia) yang mengakui kedaulatan “negara” ini. Bagaimana kisah konflik antara Azerbaijan dan Armenia ini dan mengapa “negara” ini kemudian memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri menjadi sebuah negara berdaulat bisa kamu google sendiri yah–I don’t have capacity to deal with this (isu sensitif juga soalnya, hihi).
Saat mempelajari lebih lanjut latar belakang sejarah “negara” yang namanya ear-catchy banget ini, ditambah lagi dengan iseng saya membrowsing sejumlah informasi tentangnya, saya langsung jatuh cinta saat itu juga. Nggak hanya takzim akan kecantikan bentang alamnya yang dikelilingi oeh pegunungan Ararat, perhatian saya spontan juga tertuju pada landmark ikoniknya, monumen unik Tatik-Papik yang membuat saya berandai-andai lebih jauh, what is like traveling to this “country” yah?

Monument Tatik-Papik, ikon Nagorno-Karabakh
Singkat cerita, Setelah sekitar lima-enam jam menaiki Marshrutka (angkutan umumnya Kaukasus) dan muntah-muntah berkali kali saat melintasi kelokan-kelokan maha dashyat pegunungan Ararat, tibalah saya di kota Stepanakert, ibukota dari Nagorno-Karabakh yang kini dikenal dengan nama Artsakh. Saya sengaja minta tolong pada pak sopir untuk diturunkan di kantor Kementerian Luar Negeri untuk mengurus Visa masuk. Yes, kalau biasanya kita harus apply visa dulu sebelum masuk ke sebuah negara, di “negara” ini kita masuk dulu ke negaranya baru mengurus visanya.
Adapun pengurusan visanya gampang banget. Nggak perlu bikin appointment segala, saya bisa go show ke kantornya kapan saja (jam operasional dari 08 AM- 4 PM kalau nggak salah). Begitu masuk ke dalam kantornya, saya diminta oleh sekuriti untuk mengisi selembar formulir aplikasi. Sore itu kebetulan hanya saya sendirian yang melakukan proses aplikasi visa, sehingga nggak sampai lima menit saya mengisi formulir, saya langsung diijinkan melanjutkan verifikasi dokumen di ruangan konsulat.

Gedung Kementerian Luar Negeri Artsakh
Seorang pemuda bernama Henry–kayaknya seumuran saya gitu–menyambut saya di dalam kantor dan menyilakan saya duduk di mejanya. Mas Henry mengambil paspor dan formulir yang telah saya isi, lalu menginput datanya ke dalam komputernya. Sambil menunggu ia selesai memproses visa saya, kamipun mengobrol santai. Dari beliau saya mengetahui bahwa ternyata di tahun ini, saya adalah orang kedua dari Indonesia yang berkunjung ke Artsakh. Wow, kinda surprised, karena menurut saya nggak semua orang mengetahui keberadaan “negara” ini. Dan kalaupun mengetahui, nggak semua orang “berani” mengambil resiko mengunjungi ke negara ini.
“Berapa hari kamu akan tinggal Artsakh dan rencananya akan kemana saja?” tanyanya.
“Rencananya saya cuma akan tinggal tiga hari. Saya hanya akan berada di Stepanakert dan berkunjung ke Shoushi.”
Yup, saya dan para aplikan lainnya diwajibkan untuk memberikan itinerari selengkapnya, akan berkunjung kemana saja selama di Artsakh dan kapan keluar dari Artsakh. Nggak boleh ada satu kotapun yang nggak didaftarkan karena nantinya surat ijin berkunjung yang disertakan bersama visa bakalan dicek sewaktu-waktu oleh petugas yang seliweran di setiap area. Kalau tiba-tiba kamu berkunjung ke kota/ daerah yang namanya nggak tercantum di surat itu, you’re gonna be in trouble!”
“Jadi, visanya mau ditempel di paspor atau diberikan terpisah saja?” kata Pak Henry.
“Humm….”
Ada sedikit dilema yang saya rasakan saat itu. Menempelkan stiker visa Artsakh berarti saya mengakui bahwa saya telah dengan “lancang” dan “bandel”nya melanggar batas kedaulatan Azerbaijan. Bisa dikatakan, pintu masuk resmi ke Artsakh hanya ada di batas wilayah Azerbaijan–dan pintu masuk itu telah ditutup semenjak Artsakh memerdekakan diri. Dengan memasuki Artsakh via Armenia–yang bukan merupakan border resmi–tentunya saya dianggap nggak mematuhi peraturan keimigrasian Azerbaijan yang memang lebih diakui oleh dunia. Sanksi paling tangible yang sudah pasti saya terima adalah saya bakal di-banned dari Azerbaijan. Saya nggak bisa lagi berkunjung ke negara tersebut. Sanksi yang lain? Entahlah, saya cuma bisa berdoa semoga nggak ada drama-drama lainnya selain itu, hihi.
Tapiiiiii, gue udah jauh-jauh “cari mati” masuk ke Artsakh kayak begini, masa visanya dikasih terpisah dalam lembaran kertas lainnya sih? Paspor gue nggak ketjeh dong 😀
“Attach it on my passport please.” saya tersenyum pada Pak Henry. Jadi demikianlah, visa Artsakhpun menempel manis di paspor saya–dan mulai detik ini, gue resmi ditendang oleh pemerintah Azerbaijan.

Visa Nagorno-Karabakh alias Artsakh

Visa Fee
Proses aplikasi visa selesai begitu stikernya ditempelkan. Saya dan Pak Henry saling berjabat tangan. Saya keluar dari gedung kementerian dan membuka aplikasi offline map di ponsel saya untuk mencari tahu dimana letak hostel yang saya akan inapi malam ini berada. Menurut info yang saya peroleh dari ibu pemilik hostelnya sih, lokasinya nggak terlalu jauh dari kantor Kementerian Luar Negeri.
Sembari meraba-raba pada persimpangan ke berapa saya harus berbelok kemana, saya mengamati kota Stepanakert lekat-lekat. Jujur saja, bayangan yang ada di kepala saya sebelumnya, Nagorno Karabakh bakalan berupa kota tua dengan ambians abad pertengahan dengan bangunan-bangunan batu kelabu berjajar yang membangkitkan nuansa nostalgia ala-ala kota tua Eropa. Ternyata saya salah besar. Stepanakert adalah sebuah kota modern yang tata kotanya luar biasa rapi, bersih dan teratur. Pertokoan berbaris rapi di pinggiran jalan utama beraspal mulus yang kerap dilalui oleh mobil-mobil yang berlalu lalang.
Warganya juga nggak kalah modis dan terlihat begitu ng-eropa dengan padu padanan coat musim dingin yang desainnya kekinian, boots-boots kulit yang nggak kalah ketjeh. Garis wajah Armenia yang tegas dan khas, sorot mata bulatnya yang begitu tajam dan rambut hitam yang demikian legam menjadi warisan akulturasi Eropa dan Asia yang sempurna–Yup, FYI, 90% lebih penduduk Artsakh merupakan etnis Armenia.
Dalam perjalanan mencari penginapan, saya mendadak menyadari bahwa saya sedang menjadi pusat perhatian. Orang-orang yang sedang berjalan beriringan asyik mengobrol sembari memandangi saya lekat-lekat. Ada juga yang diam-diam mengambil foto saya dari kejauhan. Duhh, apa yang salah ya dari penampilan gue?
Ketika melewati sebuah gedung tinggi, saya mendengar kasak-kusuk dari lantai atas. Begitu saya dongakkan kepala, saya mendapati dua-tiga anak kecil yang sesekali mengeluarkan separuh tubuhnya di jendela, lalu masuk lagi dan keluar lagi seperti sedang memanggil yang lainnya di dalam sana.
Benar saja, nggak lama dari itu, deret jendela lainnya yang tadinya tertutup langsung dibuka oleh serombongan anak-anak lainnya. Heboh dan kegirangan, mereka berdadah-dadah serta berhalo-halo pada saya. Karena syok dan bingung harus bagaimana, saya hanya bisa membalas lambaian tangan mereka sambil tersenyum canggung.
Dan karena kehebohan di atas sana, orang-orang yang ada di sekitar saya ikut-ikutan heboh. Semuanya menatap saya penuh dengan rasa penasaran dan berbisik-bisik antara satu dan yang lain. Yang lebih bikin syok lagi, ada seorang pemuda yang tahu-tahu turun dari mobil yang baru saja berhenti di pinggir jalan nggak jauh dari tempat saya berdiri.
“Hi how are you?” Ia menegur saya dengan ramah.
“Err… hi too, I’m fine, thanks…” saya mengernyit. Siapa orang ini?
Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. “Photo?”
“Huh?? Ok…”
Begitu saja, setelah ber-wefie beberapa kali, ia mengucapkan “thank you” dan kembali ke mobil yang sejurus kemudian melaju meninggalkan saya yang terbengong bingung. Buset, si mas-mas tadi niat banget memberhentikan mobilnya cuma buat wefie? Sejenak saya teringat akan situasi seperti ini di tanah air tercinta. Gue berasa jadi bule yang lagi terdampar di antara warga lokal.
Seperti layaknya seleb ketjeh yang berusaha menghindar dari kerumunan fans dan paparazi, saya percepat langkah saya dan segera berbelok ke salah satu persimpangan yang lebih sepi. Saya terus berjalan tertunduk saat berpapasan dengan orang yang lain lagi. Sumpah, jadi pusat perhatian kayak begini lucu-lucu risih rasanya, hihi.
Astaga, belum sampai satu jam saya berada di Artsakh, saya sudah bikin heboh satu kota. I still have 2 more days disini dan saya nggak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi beberapa hari ke depan nantinya.